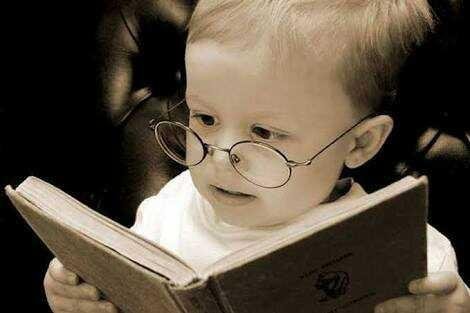
(sumber gambar: google.com)
Tulisan yang singkat ini saya maksudkan untuk menceritakan pengalaman saya ketika mulai mencoba membaca karya-karya Kuntowijoyo. Memang tulisan ini tidak mengunakan standar metodologi penelitian untuk disebut ilmiah, melainkan saya hanya mencoba untuk mengungkapkan kekaguman saya pada sosok Kuntowijoyo dengan cara menuliskan apa yang saya tangkap dari ide besar yang dituangkan Kunto dalam karya-karyanya.
Awalnya dengan tidak sengaja membaca karya-karya beliau. Saya katakan tidak sengaja, karena memang di jurusan saya kuliah, jarang saya dengar dosen saya menyebut nama Kuntowijoyo, kecuali sesekali di matakuliah sosiologi hukum islam, itupun masih mungkin. Tapi, memang, siapapunlah tokoh disebutkan oleh dosen saya ketika di kelas sudah pasti tokoh yang tidak pernah saya kenal, karena saya memang bukan seorang pembaca sebelum masuk kuliah.
Seingat saya selama sekolah, sejak Madrasah Ibtidiyah sampai Aliyah, saya baru hampir menamatkan satu buku, yaitu La Tahzan karya A’idh al-Qarni, buku yang saya pinjam dari adik kelas saya, Aqil namanya. Menurut saya dia inilah pembaca yang ulet, di dalam lemarinya menyimpan koleksi buku-buku yang tebal-tebal, tapi sekarang saya tidak tahu, apakah dia masih menjadi pembaca, semoga saja. Selain itu, saya tidak pernah membaca. Bahkan karena saking malasnya membaca, Bapak saya pernah menghadiahi saya uang jajan lebih ketika melihat saya membaca koran.
Pertama sampai ke Jogja, saya tinggal di asrama Aceh Besar, di sanalah pertama kalinya mendapat dogma bahwa ketika tinggal di Jogja adalah kesalahan besar kalau dalam satu bulan tidak membeli satu bukupun. Tapi kerena memang saya bukan seorang yang akrab dengan buku, akhirnya saya membeli buku yang saya fikir sangat membantu kuliah saya nantinya. Seingat saya, buku pertama yang saya beli adalah buku 100 Tanya Jawab Fiqih, saya lupa siapa pengarangnya, seingat saya itu disusun semacam tim dari salah satu pesantren.
Pada bulan selanjutnya, saya membeli buku di salah satu toko buku dekat ring road utara, saya kira itulah tokobuku Gema Insani. Di sana saya membeli satu buku, di covernya tertulis nama tokoh yang ketika Aliyah dahulu, salah seorang guru IPS saya menyebut Max Weber. Dan, itulah satu-satunya nama yang saya tahu tapi tidak saya kenal, apa lagi diminta menjelaskan siapa tokoh itu.
Sosiologi Agama, begitulah judulnya. Karena ukurannya yang sangat tebal, kala itu saya disindir oleh abang saya, “Untuk apa beli buku tebal-tebal, ngak kamu baca juga nanti” katanya. Saya jawab “memang bukan untuk saya baca kok, ini mau saya jadikan pengganjal pintu”. Ternyata benar, sampai sekarang buku itu belum selesai saya baca.
Awalnya saya fikir, essai-essai Max Weber tentang agama itu sebuah bacaan yang mudah, tapi saya salah telak, ternyata itu bacaan yang lumanyan dan bagi saya sangat anulah, saya tidak bisa menjelaskannya. Selain itu, saya juga membeli buku Studi Agama; perspektif out-sider dan insider, itu buku juga memuat makalah mahasiswa pasca sarjana, sehingga saya lebih mudah paham. Buku itulah nantinya sangat berguna di dalam kelas mata kuliah; Sosiologi Hukum Islam dan Oreientalisme Hukum Islam.
Pada mata kuliah Oreientalisme Hukum Islam pula kelak saya menemukan nama Edwar W Said dengan buku; Orientalisme-nya. Tapi buku itu baru saya beli setelah saya dinyatakan mendapat nilai C dalam matakuliah tersebut. Saya fikir saya akan mengulang saja di tahun depan, namun ternyata matakuliah tersebut sudah dihapuskan di jurusan Perbandingan Mazhab. Melalui buku Said, saya berkenalan dengan karya sastra, dan masalah-masalahnya ketika mengambarkan Timur dan Barat.
Lalu untuk selanjutnya saya mulai membaca dengan sengaja, yang ada di pustaka mungil saya di kontrakan Ufuweweh dan beberapa artikel, film dokumenter yang menyinggung tentang sosok Kuntowijoyo.
Saya coba lihat-lihat kembali, ternyata koleksi karya-karya Kuntowijoyo di perpus mungil kami itu, baru hanya memiliki empat karya beliau, yaitu; Budaya dan Masyarakat, buku ini termasuk buku yang sangat berkesan bagi saya, terlepas apakah saya mengerti atau tidak apa yang disampaikan di dalamnya secara utuh. Sebagai pembaca pemula, saya lebih suka menilik hal-hal yang barangkali tidak terlalu penting, semisal contoh-contoh, ketimbang kesatuan pemikiran yang ditawarkan.
Alasannya sangat sederhana, karena secara pribadi saya belum mampu menangkap apa pokok pikiran yang disampaikan, sehingga saya membaca hanya untuk menikmati, dan sekiranya dalam satu diskusi menyinggung tema terkait, saya tinggal nyeletup saja, “menurut pembacaan saya” walaupun sebenarnya saya bukan pembaca, tepatnya penonton sebuah buku.
Melalui buku yang tipis inilah saya mulai berkenalan dengan pembagian masyarakat berdasarkan musik yang mereka dengarkan. Kalau saya tidak silap dalam buku itu menjabarkan secara singkat; pemuda dalam masyarakat urban cenderung suka dengan musik dalam tempo cepat dan bersemangat, semisal musik rock ketimbang musik blues-jazz. Dari situ pulalah saya tahu kenapa musik dangdut lebih populer di kalalangan manusia urban Indonesia, ternyata musik dangdut adalah sebagai musik pemuas dan alternatif ketika musik rock dari band mencanegara dijual dengan tiket yang tak ketulungan harganya, sehingga pemuda dengan watak dinamis dan agak liar ini menyalurkannya pada musik dangdut.
Di samping itu, juga dikenalkan perbedaan budaya keraton dan budaya populis; mulai dari bahasa krama inggil dan tembang-tembang yang diproduksi oleh keraton dengan pujangga-pujangga istanya, juga dikenalkan dengan bahasa masyarakat sepaket dengan tontonan ketopraknya. Sehingga ketika selesai membaca buku itu, saya pernah berkeinginan menonton tari kraton, atau tari-tarian yang sering diadakan di Prambanan pada bulan bagus. Tapi sampai tulisan ini saya tulis, saya belum pernah menyaksikannya, tentu oleh beberpa alasan; pertama ada tarian yang dibuka untuk tourism mancaranegara, yang tentunya jika saya memaksakan diri untuk hadir berarti saya harus berpuasa selama sebulan penuh, artinya uang masuk sama dengan uang jajan saya selama sebulan.
Terlepas dari hal itu, inilah yang membuat saya jatuh cinta dengan Jogja. Jika sekiranya Belanda disebut-sebut; apa yang terdapat dalam cerita dongeng bisa kita temui di Belanda, maka di Jogja apa yang baru saja kita baca dalam buku bisa kita temui di Jogja. Sehinga apa yang baru saja kita baca rasanya sangat dekat, dan setidaknya masih bisa divisualkan. Ketika misalnya dalam satu buku menceritakan kraton, imajinasi tentang kraton itu sudah bisa dibayangkan, setidaknya dari segi bangunannya. Hal ini pulalah membuat saya iri pada Jogja, karena di tempat saya belum menemukan bacaan yang mebuat saya dekat dengan apa yang saya lihat sehari-hari. Ketika membaca sejarah Aceh, entah mengapa saya seolah diantarkan pada zaman dan negeri yang jauh.
Memang saya bukan pembaca yang ulet dan tekun. Sependek ini saya baru menemukan satu bacaan; buku Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad dengan Aceh Baru Post-tsunami, dan Acehnologi-nya beliau; itupun terbatas pada sub pembahasan antropologi dan sosiologi Aceh saja, karena jika bebicara sejarah dan sejarah pemikiran, entah, saya rasa saya berada di rentang waktu yang jauh. Mungkin inilah yang disebut jurang-intelektual yang terjadi di Aceh; di mana konflik disebut-sebut pemutus matarantai, atau jika frasa putus terlalu ekstrim, mungkin sebutan pincang lebih cocok; perjalanan intelektual itu tetap ada, tapi kerap tidak mampu bersaing dalam lomba lari.
Entahlah, apakah memang suatu yang wajar atau tidak sekiranya intelektual dan tulisan-tulisan yang berkembang di Aceh banyak yang berbau post-kolonial, padahal Belanda-Jepang sudah pulang ke kandang tak jauh setelah proklamir kemerdekaan. Walau memang kajian post-kolonialisme itu luasnya minta ampun, kata senior saya yang fokus pada sastra. Eh, tapi pun begitu, katanya, post-kolonialisme secara singkat bisa kita pahami karya atau apalah yang lahir dalam atau pasca kolonial.
Saya tidak tahu, apakah di garda Timur juga melahirkan bau intelektual, tulisan dan karya seni yang sama? Sekiranya ada pola yang sama, adalah sah dalam kitab sejarah nasional tertulis; bahwa Indonesia pernah menyayat jarinya sendiri, meski mengupas manggalah alasannya. Kalau mahu tau “seni pembunuhan” saya sarankan panjenengan baca itu; Aceh Bersimbah Darah karena setelah membaca buku itu, entah mengapa saya semacam melihat jenis dan cara-cara pembunuhan dilaksanakan.
Semakin ke sini, tulisan inipun semakin meleber. Tapi begitulah sebuah tamasya. Istilah tamasya intelektual pertama sekali saya kenal dari karya Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, jika beliau bertamasya dalam keilmiahan, saya hanya baru mampu di pinggir-pinggirnya saja. Seperti hal bertamasya, saya yakin ketika bertamasya kita kerap menceritakan apa yang tidak ditanyakan sekalipun. Misalnya kita akan bercerita tentang pengamen, air terjun, kucing liar, kucing panjang dan lain sebagainya.
Ya, saya fikir begitulah tulisan inipun. Awalnya saya berniat untuk hanya menulis Kuntowijoyo dan karya-karyanya, tapi dalam bertamasya ternyata Kuntowijoyo malah mengantarkan saya pada tempat-tempat asing, sebutlah; Ilmu Sosial Profetik, Sastra Profetik, dan lain sebagainya. Meski saya sudah membaca tapi saya masih bingung, itu profetik seperti apa? Sebuah wahana yang menantang adrenalin kah?
Setelah sekian lama tidak membaca buku, saya mencoba untuk membaca kembali, terutama tulisan-tulisan mengenai Ilmu Sosial Profetiknya Kuntowijoyo. Ternyata benar, paradigma profetik itu sangat menantang adrenalin saya sebagai seorang mahasiswa krasak-krusuk ini, betapa tidak, setelah petama kali dikenalkan doktrin sosiologi sebagai ilmu yang non-etis, kata guru saya dulu, sebuah doktrin yang barangkali tidak disetujui oleh Kuntowijoyo sendiri. Tapi, tentu teks-teks Kuntowijoyo tidak lagi mampu melarang saya, melainkan hanya sebagai pengarah; ketika tiba di tempat wisata itu saya harus bagaimana.
Entah karena memang keterbatasan referensi atau karena kemalasan dalam penelaahan, saya belum menemukan pada halaman berapa tetang musik sebagai penanda kelas sosial adalam masyarakat itu dalam buku Kuntowijoyo. Saya sudah coba baca indeksnya, ternyata tidak ada, atau saya yang kurang cermat. Tapi, seingat saya hal itu memang ada, saya lupa pada halaman berapa dan pada bab berapa. Agaknya teman-teman bisa membaca buku itu sendiri, tapi yang edisi paripurnanya. Jika semisal, apa yang saya sebut musik dan kelas sosial itu tidak ada dalam buku tersebut, maka saya mohon secepat kilatlah teman-teman membantah tulisan ini agar tidak menjadi hoax di kalangan Kuntoisme.
Banyak hal untuk mencintai karya-karya Kuntowijoyo, sebutlah salah satunya keunikan dan keringanan gaya bahasa yang beliau gunakan. Sebagai seorang yang bukan kritikus, tentu aku hanya mampu menikmati tanpa mesti mengerti kategorisasi yang disematkan padanya.
Membaca cerpen-cerpen Kuntowijoyo, memberikan harapan baru tentang pandangan hidup; aku merasa lebih ringan saja melihat fenomena yang rumit-tumit, urat ketawa selalu dipacu, sampai kita menemukan kenikmatan sebuah cerita.
Saya kira basik Kunto sebagai akademisi yang konsen dalam ilmu sejarah disamping sosial-budaya menjadikan karya sastra beliau sebagai karya yang padat dan penuh, di mana ruang basa-basi setting dipangkas seringkas-ringkasnya, tapi tetap mampu dinikmati sebagai sebuah karya sastra yang sedap. Apa lagi dengan gaya pemotongan yang curamnya. Jangan kaget ketika mendapati cerita yang gantung, yang mungkin memang dengan sengaja agar para pembaca memikirkan kelanjutannya.
Sekian bulan saya coba menyelam dalam cerpen-cerpen beliau, sampai saya rasa saya memang benar-benar hanyut. Dengan gaya bercerita layaknya tutur biasa, sehingga cerpen beliau menjadi sangat dekat dan tidak membosankan ketimbang cerita dengan setting dan alur yang kadang terlalu dipaksakan untuk memenuhi hasrat agar atau malah biar dianggap sastrawi.
Pada akhirnya tulisan ini tidak ubahnya cerita seorang yang tersesat ketika bertamasya dalam bacaan-bacaan. Ketika menemui karya Kuntowijoyo, adalah tidak mungkin untuk tidak menemukan karya yang lain pula di dalamnya. Ya, sebagai sebuah tulisan orang yang “tersesat” ketika berjalan-jalan, maka tulisan ini melompat-lompat barangkali.
Sebenarnya saya ingin merampungkan dengab agak lebih waras, tapi inikan untuk steemit.com, dimana penulis dikejar jadwal tanyang. Eh, keceplosan. Hehe. Krohkrohkroh.
Bila masanya tiba, saya memang dan memang berniat untuk menulis lanjutan tulisan ini, karena belum satu bukupun yang dengan fafifu saya beberkan di tulisan ini. Selamat bertamasya, selamat membaca, cinta.
Emmuah.
Yi Lawe.
Jogjakarta, 2018.
Tulisan anda sangat menarik dan fantastik. Terimakasih telah berbagi ilmu dan informasi, semoga tulisan ini juga bermanfaat bagi orang lain. Suksessss...
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Terimakasih, Pak. Krtikik dan sarannya, sangat kami butuhkan. :)
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Congratulations @yilawe! You received a personal award!
Click here to view your Board
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Congratulations @yilawe! You received a personal award!
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit